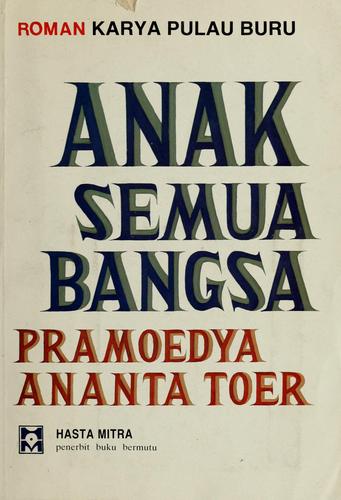Buku ini bercerita, sejauh yang saya tahu, tentang seorang sosok pribumi (Minke) yang sebelumnya telah dididik dengan pendidikan Belanda melihat sendiri kehidupan masyarakatnya yang saat itu tidak berdaya-upaya melawan kekuatan Eropa. Di sini Minke dihadapkan pada situasi yang dilematis. Satu sisi ia melihat betapa peradaban Eropa begitu tingginya dan membuatnya dapat berkembang menjadi manusia yang berkualitas.
Anak Semua Bangsa merupakan buku kedua dari tetralogi Buru. Sama seperti buku pertama, buku ini ditulis Mas Pram saat meringkuk di penjara Pulau Buru. Naskah ini pun ia share dan bacakan kepada mereka yang dipenjara.
Di sisi lain, ia melihat masyarakat pribumi begitu
mengibakan dan kerdil di hadapan sistem dan hukum Negeri Penjajah. Suatu
hal yang sangat disayangkan dan tentunya tak bisa berbuat apa-apa untuk
saat ini.
Sebelumnya memang ada perbedaan pandangan antara Minke dengan
kawan-kawan hidupnya—Kommer, Jean Marais, Bunda Minke, dan Mama (Nyai
Ontosoroh)—tentang kehidupannya dan kehidupan pribumi baginya. Minke
merasa bahwa orang-orang Pribumi kecil itu tak pantas diajak berbicara
soal Hindia dan tak dapat merasai negerinya—karena bodoh, tak
bersekolah, tak dapat berhitung dengan baik, serta keterbelakangan yang
tak pernah mereka dan Minke harapkan. Sedang menurut Kommer dan
kawan-kawan hidupnya yang lain, adanya berita bertuliskan Jawa, Melayu,
dan bahasa-bahasa Pribumi di Hindiamenandai bahwa kepedulian
Minke terhadap bangsanya sungguh mencuat [ganti kata mencuat ini].
Yang
ingin segera saya garis bawahi di sini adalah setiap kekalutan dan
ketakutan yang dirasa oleh pribumi merupakan ketakutan setiap manusia
yang ada di dunia, bukan saja di Hindia. Bahwa Kolonial terlalu pengecut
meneror Pribumi dari masa ke masa sehingga dalam alam bawah sadar
mereka terpatri kuat: Bangsa Kulit Putih lebih terhormat dan lebih
berjaya ketimbang pribumi sendiri di tanahnya. Ini sungguh mengibakan.
Eropa memang lebih unggul dari Hindia, tapi tidak di segala hal. Jangan agungkan mereka seperti dewa.
Politik Etis adalah politik balas budi yang ditetapkan Belanda
terhadap Hindia. Ini dilakukan untuk memberikan suatu balas-jasa atas
segala tindak-penjajahan Kompeni sehingga Hindia tidak hanya menjadi
daerah yang “habis manis sepah dibuang” tetapi menjadi daerah jajahan
yang maju dan hebat [ganti nih kata hebat di sini, ga keren]. 3
program politik ini pun dibuat: Edukasi, Emigrasi, dan Migrasi. Edukasi
adalah program pendidikan kepada penduduk pribumi agar pandai dan bisa
bersekolah layaknya orang-orang Indo, Peranakan, atau Totok. Emigrasi
adalah program yang mengajak warga di wilayah padat penduduk untuk
bertransmigrasi ke wilayah yang masih tidak padat penduduknya. Sedangkan
Irigasi adalah program pengairan untuk keperluan pertanian tiap
penduduk yang memiliki/mengolah lahan pertanian.
Program yang sangat bagus dan membangun. Namun rupanya ada udang di
balik batu. Program-program ini sesungguhnya adalah proyek terselubung
pihak Belanda untuk terus mengeruk keuntungan dalam kesempatan yang
lebih besar. Kebijakan-kebijakan yang awalnya diajukan oleh van Deventer
tersebut memang terlihat sangat baik dan menawan hati. Tapi pada
hakikatnya program ini adalah mengenai kepentingan gula.
Secara garis besarnya, program terselubung ini sudah dapat ditebak.
Mengingat Jawa sebagian besar memiliki tanah yang subur dan lahan
pertanian yang luas. Selain itu, kebijakan Pemerintah Belanda saat itu
menitikberatkan pada ketersediaan gula, yang mana sangat bernilai
harganya di mata Eropa pada saat itu. Praktis petani gula adalah profesi
yang sangat populer di kalangan para petani.
Dalam kenyataannya, ketiga program itu tidaklah berjalan semestinya (sudah dapat diduga!).
Program Edukasi yang katanya bakal mendidik pribumi nyatanya hanya
seputar baca-tulis & hitung-menghitung, yang mana justru bertendensi
dan menjurus kepada apa-apa yang terkait dengan administrasi produksi
gula.
Begitu pun dengan Emigrasi. Program pemerataan penduduk ini, yang
seharusnya mengajak warga di wilayah padat penduduk untuk pindah ke
daerah yang tidak padat, justru dipaksa untuk pindah ke daerah
yang memiliki lahan pertanian gula. Mungkin takkan menjadi masalah jika
hasil kerjanya sesuai dengan upah. Ketidakadilan ini memang kekejian
yang tak terlihat oleh pribumi yang tak melihat langsung turun ke
arus-bawah. Tidak jauh berbeda dengan kedua program tadi, Imigrasi yang
digadang-gadang untuk mengairi lahan pertanian pribumi justru dimonopoli
(lagi-lagi) untuk kepentingan gula. Pengairan tersebut sesungguhnya
memang untuk pertanian gula dan tebu sahaja. Dan yang bikin tambah
ngenes, hasil pertanian itu sebagian besarnya masuk ke kantong
Pemerintah Penjajah.
Setelah melihat sendiri kehidupan petani gula dan tebu di Tulangan
Sidoarjo kesadaran Minke pun tersentak. Ketidakadilan yang begitu
kentara (jika saja ia punya niatan dan sedikit usaha untuk melihatnya)
tenyata membikin kehidupan pribumi begitu sengsara. Hati nurani dan
nasionalismenya pun tergugat, tergurah, dan tergugah untuk menyelesaikan
kecurangan ini. Ia tersadar akan satu hal, bahwa ia adalah bayi semua
bangsa dari segala jaman yang harus menulis dalam bahasa bangsanya
(Melayu) dan berbuat untuk manusia-manusia bangsanya.
Deskripsi Mas Pram terhadap sejarah adalah deskripsi yang asosiatif,
imajinatif. Kalimat-kalimat yang beragitasi sebagai stimulan
nasionalisme itu bahkan sungguh deras bak terjunan air niagara yang tak
ada habisnya. Saya melihat Mas Pram jujur dalam menulis dan merangkai
ceritera yang
mengangkat sejarah di awal-awal Kebangkitan Nasional ini.
Saya tidak ingin terjebak dalam romantisme sejarah yang kabur dan membingungkan. Meski anggota Lekra (yang telah di-judge bersalah
karena bagian dari Partai Komunis Indonesia), Mas Pram saya lihat
sebagai sosok anak bangsa Indonesia yang menginginkan negerinya bebas
dari jeratan penjajahan yang ada, baik yang berupa sistem atau yang
berwujud yang lainnya. Ia manusia berpikiran merdeka yang ingin melihat semua ini berakhir. Bahwa Indonesia merdeka seutuhnya adalah harga mati baginya! Bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa Indonesia!
“Kita sudah melawannya nak, Nyo! Sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya” Nyai Ontosoroh.